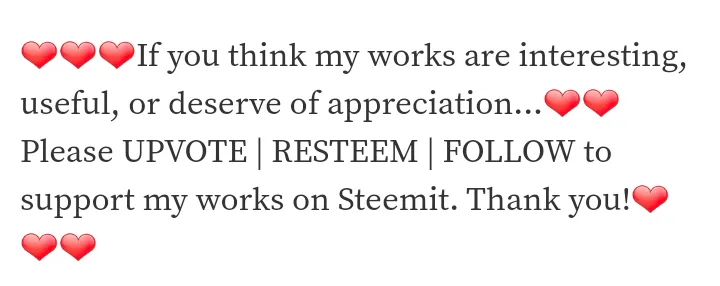“The true bearers of ideology in art are the very forms, rather than abstractable content, of the work itself.”[1]
(Georg Lukács)
Sebagai salah satu bentuk seni tertua, puisi merupakan suatu cara untuk bereaksi terhadap dunia. Ia merupakan suatu visi, suatu pernyataan sikap yang kadang bisa menjadi sangat politis. Namun kadang ia juga dapat menjadi suatu aktivitas yang membosankan, suatu aktivitas yang terasa ‘sia-sia’. Pemikiran ini muncul terutama setelah membaca puisi-puisi yang akhir-akhir ini muncul di berbagai media massa, yang pada akhirnya menimbulkan suatu pertanyaan: apakah seorang penyair pernah merasa bosan dan kemudian malah mencaci-maki puisi-puisinya sendiri?
Pertanyaan ini berkelebat dalam benak ketika saya merasa bahwa puisi-puisi yang ada akhir-akhir ini—puisi-puisi tahun 1980-an dan 1990-an sampai sekarang—hanya mengulang-ulang apa yang telah dituliskan oleh penyair-penyair sebelumnya, yang dapat dikatakan sebagai penyair-penyair yang “sudah mapan”. Saya merasa puisi-puisi tersebut telah terjebak dalam suatu rutinitas bentuk dan gaya pengucapan dari penyair-penyair yang “sudah mapan”. Dan rutinitas, selain menimbulkan rasa bosan, juga menimbulkan apa yang dalam bahasa Jawa disebut ampang. Tidak terasa lagi adanya percobaan-percobaan kreatif—seperti yang pernah dilakukan oleh para penyair tahun 1970-an—yang penuh ketakerdugaan. Tak ada “kegaduhan” yang kadang membuat kita tercengang. Saya merasa bahwa sebagian besar puisi-puisi tersebut telah terjebak dalam apa yang oleh Goenawan Mohamad (GM) disebut sebagai machiavelisme kesusastraan[2] — dalam hal ini puisi.
Seorang machiavelis, demikian GM, dalam bentuknya yang lebih kecil adalah seorang pengarang yang mempertaruhkan nilai karyanya mutlak kepada tema (isi/pesan) karangannya. Bagi saya, kategori machiavelis ini juga dapat diterapkan pada para penyair yang hanya megadopsi bentuk-bentuk puisi yang telah didedahkan oleh penyair-penyair pendahulunya yang ada dalam tradisi sastranya. Para machiavelis ini, tanpa usaha atau percobaan-percobaan pencarian bentuk bagi tema (isi/pesan) yang hendak disampaikan, memandang tema (isi/pesan) sebagai tujuan akhir dan satu-satunya di mana semua karyanya dipertaruhkan. Keadaan ini tentu akan menimbulkan kesan bahwa apa yang terasa dalam karya atau puisi-puisi mereka bukannya proses kreasi, melainkan hanya proses adopsi. Keadaan ini—saya membayangkan—nantinya akan menyebabkan terjadinya kemandekan dalam tradisi puisi.
Kemandekan dunia puisi yang terjadi dewasa ini, seperti yang telah sedikit disingung di atas, lebih disebabkan para penyair kurang berani melakukan penjelajahan dan percobaan dalam bentuk dan gaya pengucapan puisinya. Dengan bentuk dan gaya pengucapan yang relatif tidak berbeda antara satu puisi dengan puisi lainnya, antara satu penyair dengan penyair lainnya, saya khawatir—dan sering membayangkan—puisi akan segera ditinggalkan. Sebab dengan hanya bersandar pada tema (isi/pesan), orang dapat saja mencarinya di tempat lain: majlis ta’lim, kitab-kitab suci, khotbah-khotbah moral para politisi, atau pesan-pesan sosial para petinggi negeri.
Memang, mungkin machiavelisme kesusastraan ini masih bisa diterima ketika pandangan terhadap puisi masih seperti yang diungkapkan oleh John F. Kennedy saat ia membaca Longfellow dan John Greenleaf Whittier, atau pandangan Soe Hok Gie ketika membaca Walt Whitman dan Chairil Anwar—dalam pandangan mereka puisi dapat menjadi tempat penyucian bagi kekotoran politik; atau, dengan kata lain, menjadi “pengisi jiwa” dari seorang ahli jiwa.
Namun posisi puisi menjadi lain ketika pandangan terhadap puisi juga telah menjadi lain. Posisi puisi menjadi lain ketika puisi tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang misterius, dan dianggap sama dengan teks-teks lain. Posisi puisi menjadi lain ketika ucapan Stalin bahwa “pengarang (atau penyair) adalah insinyur jiwa manusia” sudah tidak dapat dipertahankan lagi.
Di sini tidak berarti kita harus memandang rendah tema (isi/pesan) dan terlalu mengelu-elukan bentuk layaknya penganut L’art pour l’art atau Kaum Formalis Rusia. Hanya saja, terlalu berkutat pada tema (isi/pesan) hanya akan menjadikan puisi tak ubanya seperti pesan-pesan moral, khotbah-khotbah keagamaan, atau seruan-seruan sosial seperti yang telah disebutkan di atas. Padahal, meminjam ungkapan Lascelles Abecombrie, beranggapan bahwa bahwa fungsi sastra (baca: puisi) adalah untuk mengajar manusia agar lebih bermoral berarti sudah melangkah keluar dari sastra itu sendiri. Terlalu berkutat pada tema (isi/pesan)—dengan dalih mencari “kedalaman”, misalnya—akan menjadikan puisi hanya sebagai alat atau sarana untuk menyampaikan suatu pesan dan tidak dihargai pada dirinya sendiri.
Dari apa yang diungkapkan di atas, tidak berarti kita harus memandang bentuk dan tema (isi/pesan) sebagai dua hal yang dapat dengan jelas dipisahkan seperti layaknya anggur merah dan gelas. Namun, bagi penyair yang telah menemukan bentuk pengucapannya sendiri—penyair-penyair yang benar-benar terlibat dan merasakan proses kreasi dan penjelajahan kemungkinan-kemungkinan pengucapan—adanya jarak antara bentuk dan tema (isi/pesan) sangatlah terasa. Terry Eagleton mengungkapkan bahwa “if form and content are inseparable in practice, they are theoretically distinct” (Terry Eagleton, 1984, hal. 24). Menolak adanya jarak antara bentuk dan tema (isi/pesan), secara tidak langsung berarti menolak adanya pilihan-pilihan pengucapan.
Kemandekan yang muncul dari “kemiripan” bentuk dan gaya pengucapan ini setidaknya dapat dilihat dalam fenomena berikut: dekade 1980-an dan awal 1990-an dalam dunia perpuisian di Indonesia boleh dibilang merupakan masa di mana banyak sekali lahir nama-nama penyair. Masa ini menunjukkan betapa iklim penulisan puisi mencapai titik paling subur. Namun, anehnya, di antara sekian banyak nama penyair baru, hampir tidak terlihat karya-karya yang memunyai gaung yang luas dan bertahan lama. Memang, dalam dekade-dekade tersebut juga muncul pembaruan. Namun pembaruan-pembaruan yang terjadi lebih memberi penekanan pada tema (isi/pesan)—dalam dekade tersebut muncul kecenderungan kuat untuk mengangkat tema-tema sufistik dan menjadikan tradisi sebagai sumber ilham penciptaan. Danarto menyebut kecenderungan ini sebagai gerakan “kembali ke sumber”, sedangkan Sutardji Calzoum Bachri menyebutnya sebagai gerakan “kembali ke akar tradisi”. Sayangnya, pembaruan dalam tema (isi/pesan) tersebut tidak ‘dibungkus’ dalam bentuk dan gaya pengucapan yang juga baru.
Fenomena di atas sangat berbeda dari apa yang terjadi dalam dekade 1970-an. Dalam dekade ini dunia perpuisian di Indonesia terasa begitu riuh dengan beragam bentuk dan gaya pengucapan yang coba ditawarkan: ada Sapardi Djoko Damono dengan puisi imajinya; ada Remy Sylado dengan puisi ‘mbeling’-nya yang mencoba membongkar puisi sebagai sesuatu yang dianggap serius dan luhur; ada Goenawan Mohammad dengan puisi ‘suasana’ dan puisi ‘intelektual’-nya; dan lain sebagainya. Dalam dekade ini, di mana nama-nama penyair yang muncul tidak sebanyak seperti yang terjadi dalam dekade 1980-an dan 90-an, juga muncul suatu pembaruan yang sangat penting yang kemudian menjadi salah satu tonggak atau genre tersendiri dalam dunia perpuisian di Indonesia: Sutardji Calzoum Bachri dengan puisi ‘mantra’-nya. Mungkin dari segi tema (isi/pesan), puisi mantra Sutardji (yang terkumpul dalam O, Amuk, Kapak) relatif tidak jauh berbeda dari tema (isi/pesan) yang tertuang dalam puisi-puisi penyair lainnya (tema cinta, ketuhanan, kemanusiaan, dan sebagainya). Namun dari tema (isi/pesan) yang ‘biasa’ dan relatif sama ini dapat muncul suatu gaung yang sangat luas dan bertahan lama. Dan gema atau gaung tersebut, seperti dapat kita lihat, muncul lebih karena bentuk dan gaya pengucapan puisinya yang baru—termasuk metafor dan simbol-simbol yang digunakannya—yang pas dengan kredo puisi yang dituliskan dalam bukunya tersebut.
Dari sini kita dapat melihat bahwa kekuatan sebuah puisi bukan hanya bergantung pada tema (isi/pesan) yang ‘universal’, ‘suci’, dan ‘memberat’, melainkan juga (dan terutama) pada bentuk dan gaya pengucapannya yang khas, ‘baru’, dan unik. Memang, meminjam ungkapan Hegel dalam Philosophy of Fine Art, “setiap isi memunculkan bentuk yang cocok dengannya.”[3] Namun hal ini bukan berarti tanpa disertai dengan pencarian dan percobaan bentuk-bentuk dan gaya pengucapan yang baru. Karena, seperti yang dikutip di awal tulisan ini, “the true bearers of ideeology in art are the very forms, rather than abstractable content, of the work itself.”
Daftar Rujukan:
Terry Eagleton, Marxism and Literary Criticism, London: Routledge, 2002, hal. 23.
Goenawan Mohamad, Kesusastraan dan Kekuasaan, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993, hal. 83-85.
Terry Eagleton, Marxism and Literary Criticism, London: Routledge, 2002, hal. 20.
Original Essay by Zaim Rofiqi
With Love...☕❤
ZR
==================